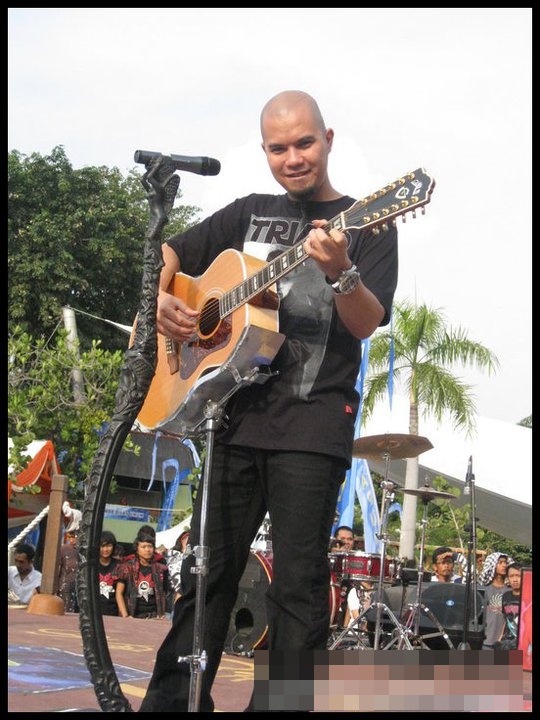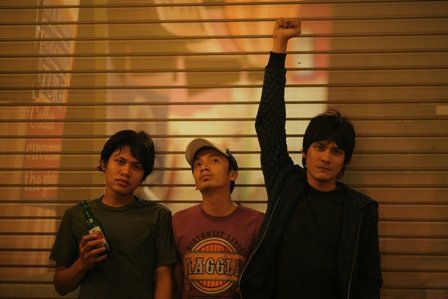Hari masih sore, tapi makam
(pesarean) syeikh Ahmad Mutamakkin –masyarakat Kajen, Pati, Jawa Tengah
lebih akrab menyebutnya mbah Mad- kembali sesak dengan jubelan manusia.
Satu persatu mulai memasuki pekarangan berukuran 6×14 meter yang lebih
tampak seperti bangunan masjid itu. Setelah sebelumnya mengambil air
wudlu di tempat yang tersedia, para pengunjung segera mengambil kitab
Alquran, mulai duduk hikmad, secara lirih melantunkan bacaan ayat demi
ayat sampai rampung. Tapi, tidak sedikit pula yang benar-benar
menghabiskan satu hari satu malam tafakkur, ngaji, dan bertawassul di
tempat itu. Pemandangan seperti ini memang biasa disaksikan di pesarean
Mutamakkin atau mungkin juga di tempat-tempat lain yang dianggap
memiliki sejarah dan nilai karomah tertentu. Datang silih berganti,
laki-laki dan perempuan yang mengaku dari berbagai pelosok Pati dan
sekitarnya itu memang sengaja menyempatkan diri sowan, ziarah, kirim
doa, atau bermunajat di hadapan makam sang syeikh. Biasanya, para
peziarah mulai berdatangan pada Kamis siang dan berakhir pada Jum’at
sore. Meskipun makam tersebut disinyalir sudah berumur + 200 tahun,
tetapi sawaban, keramat, dan pesona kesucian yang terpancar dari sosok
Ahmad Mutamakkin masih dirasakan sampai sekarang. Bahkan, makam yang
berdekatan dengan Madrasah Mathali’ul Falah pimpinan KH Sahal Mahfudz
itu pun dijadikan oleh para santri (laki-laki) sebagai tempat untuk
berkhalwat, nyepi, dan menghafal Alquran. “Di sini lebih nyaman dan
lebih tenang. Jadi bisa konsentrasi untuk ngapalin Alquran, Mas,” ujar
Muhammad Ihsan (14 tahun), santri Mathali’ul Falah.
Tampaknya,
fenomena makam ulama asal Cebolek tersebut semakin jelas memangkirkan
asumsi dan/atau bayangan tentang pada umumnya makam yang identik dengan
nuansa seram, angker, dan menakutkan. Santri, masyarakat sekitar, dan
tamu peziarah justru menjadikannya sebagai ajang untuk memohon sesuatu
kepada Sang Khalik justru melalui perantaraan (wasilah) jasad beku
Mutamakkin. “Ya, seminggu sekali, khususnya malam Jum’at saya hampir
pasti ke sini. Kadang-kadang sendiri, tapi sering juga dengan
teman-teman yang lain. Saya ngaji beberapa ayat, setelah itu berdoa.
Mbah Mad itu kan waliyullah, punya karomah. Jadi melalui doa itu
mudah-mudahan kita juga mendapat berkah,” ujar Suseno (44 tahun), salah
satu warga Kayen, Pati Selatan.
Selain
makam, tempat lain yang juga dijadikan tempat perenungan dan berkhalwat
adalah Masjid Ahmad Mutamakkin, 100 m ke arah timur dari makam beliau.
Masjid kuno –konon usianya + 250 tahun- yang saat ini lebih popular
disebut dengan masjid jami’ Kajen ini juga menjadi tempat bertujunya
para peziarah dari berbagai tempat. Di dalam masjid terdapat beberapa
bagian bangunan seperti mimbar, dairoh (langit-langit dalam masjid),
papan bersurat di samping tempat pengimaman shalat, dan palang pintu
masjid yang diyakini hasil kreasi Ahmad Mutamakkin. Dan beberapa kreasi
Mutamakkin itu banyak dimaknai orang sebagai karya yang memiliki nilai
filosofis yang tinggi. Misalnya, di mimbar terdapat ornamen, ukir-ukiran
dengan salah satunya bentuknya adalah bulan sabit yang dipatuk burung
bangau. Motif ini dimaknai sebagai semangat dan doa Mutamakkin terhadap
keturunannya (termasuk keturunan simbolis/penerus perjuangannya) akan
bisa mencapai cita-cita mulia. Lalu terdapat ukiran bunga yang tumbuh
dari tunas sampai mekar yang juga diyakini masyarakat sekitar sebagai
doa pencapaian khusnul khatimah bagi keturunannya, sebagaimana terdapat
dalam papan bersurat “sing penditku ngusap jidatku”, yang termasuk
keturunanku, mengusap jidatku (Bizawie, 2002: 107).
Di
samping itu, masih terdapat sumur yang juga diyakini sebagai sumurnya
Mutamakkin. Sumur ini terletak sekitar 2 km sebelah timur dari Kajen,
tepatnya masuk ke dalam desa Bulumanis. Sumur ini tidak pernah kering
dan masyarakat sekitar sangat yakin bahwa air sumur tersebut bisa
mengobati beberapa penyakit.
Tentu,
selain adanya pondok pesantren –di Kajen terdapat sekitar 35 pondok
pesantren dan 4 madrasah- tempat-tempat inilah yang telah membuat
ratusan bahkan ribuan orang datang ke Kajen. Apalagi, setiap tahun pada
tanggal 10 Suro (Muharram) makam Ahmad Mutamakkin bisa dipastikan penuh
dengan ribuan peziarah karena tanggal ini telah ditetapkan sebagai haul
(peringatan tahunan) Mutamakkin. Pak Sholeh (37 tahun), juru makam
Mutamakkin menuturkan bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada tempat
sedikit pun yang longgar dari pengunjung. “Wah, jumlahnya bisa sampai
10.000 orang. Makanya seluruh tempat makam sampai ke ujung jalan Kajen
ini sesak oleh peziarah, Mas,” tutur kuncen muda ini. Salah satu
fenomena menarik yang selalu menjadi rutinitas ritual haul adalah adanya
momen khusus dimana kain putih penutup makam Mutamakkin dilelang secara
umum. Keseluruhan kain yang diyakini mengandung kekuatan magis ini
pernah dijual sampai menghasilkan uang sebanyak 70 juta rupiah.
“Sepertinya yang kebanyakan membeli kain itu para nelayan karena mereka
sangat yakin kalau perahunya itu ditempeli kain itu, rata-rata
penghasilan ikannya banyak terus,” tutur Pak Sholeh.
Memang
satu hal yang bisa dibaca dari efek haul seperti itu adalah penciptaan
kontinuitas pesona mitis yang diharapkan akan selalu diingat oleh siapa
pun yang datang ke pesarean Mutamakkin. Haul dikonstruksi sedemikain
rupa –entah sadar atau tidak- bertujuan untuk menghadirkan daya linuwih
yang dimiliki oleh tokoh yang sudah meninggal sekaligus untuk
melegitimasi kekuasaan para keturunannya. Dalam konteks ini, fenomena
jubelan ratusan bahkan ribuan orang itu mungkin dan hanya mungkin
terjadi karena masyarakat melihat adanya sesuatu yang masih patut dipuja
sebagai panutan yang memiliki kelebihan, karomah, dan berkah. Persoalan
bahwa apakah kirim doa itu mengharuskan para peziarah untuk menengok
terlebih dahulu ke belakang, ke sebuah masa dimana Mutamakkin melakukan
gerakan kultural keagamaan di Kajen bukanlah hal utama. Peziarah juga
tidak terlalu penting untuk melihat bahwa Ahmad Mutamakkin pernah
diceritakan oleh Raden Ngabehi Yasadipura I sebagai sosok yang
menyebarkan ajaran “sesat,” menggaungkan konsep manunggaling kawula lan
gusti ala Siti Jenar atau seperti hulul ala al-Hallaj, layaknya
“penyimpangan syariah” yang dilakukan Sunan Panggung, Ki Ageng Pengging,
dan Syeikh Amongraga. Mungkin seperti itulah fenomena Mutamakkin yang
juga disambut oleh Ketib Anom Kudus sebagai pembelokan syariat yang
membahayakan publik. Bagi peziarah, terdapat hal lain yang lebih penting
dari persinggahan di depan makam adalah bagaimana bisa merasakan
kehadiran Mutamakkin dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai
sosok tetapi juga sebagai tokoh penyebar Islam pertama di Kajen dan
penghubung antara keinginan masyarakat dengan Tuhan.
Di samping itu, endapan benak mayoritas masyarakat Kajen meyakini
bahwa perdebatan Mutamakkin dengan Ketib Anom itu pun pada hakikatnya
bukan dimenangkan oleh ulama asal Kudus itu, melainkan oleh Mutamakkin
sendiri. “Lho, mbah Mad itu kan ilmunya sudah mencapai tahap tinggi,
jadi Ketib Anom itu tidak bisa memahami ungkapan-ungkapan mbah Mad lalu
diisukan kalau mbah Mad itu tidak bisa apa-apa. Maklum, Ketib Anom itu
kan tingkatannya masih syari’at, jadi kalah kuat kalau harus berhadapan
dengan mbah Mad,” demikian tutur pak Sholeh. “Wah tidak benar kalau mbah
Mad itu menyebarkan ajaran manunggaling kawula lan gusti atau ajaran
sesat lain, anti syariat, atau apa itu. Masjidnya itu kan bisa jadi
bukti bahwa beliau juga menjalankan syariat, karena di masjid itulah
beliau melaksanakan shalat dhuha, shalat jumat, dan shalat fardlu yang
lain,” tandasnya kemudian.
seperti
pembelajarannya yang mumpuni menguasai serat Dalam pandangan pak Sholeh
perdebatan Mutamakkin dengan Ketib Anom Kudus merupakan cermin dari
ketidakrelaan kelompok agama pembela keraton melihat tingkah laku
Mutamakkin yang nyeleneh, tidak patuh pada raja, sampai dianggap fasik
karena memelihara duabelas anjing. Mungkin persoalannya bukan hanya
sebatas itu. Keunggulan Mutamakkin, seperti diceritakan oleh pak Sholeh,
adalah kemampuannya untuk mengawinkan ajaran kejawenDewaruci dengan
ajaran Islam Timur Tengah, sebuah laku kreatif untuk menghidupkan ajaran
lokal di samping ajaran Islam Arab. Dengan kata lain, tidak mudah bagi
Ketib Anom untuk menyaksikan kemungkinan terjadinya peleburan Islam
dengan lokalitas yang ia anggap akan berakibat pada penodaan terhadap
ajaran Islam yang “murni.” Maklum, Ketib Anom atau juga ulama lain yang
berafiliasi ke keraton waktu itu merasa sebagai penanggungjawab dan
pengatur persoalan kehidupan sosial, politik, budaya, dan agama. Ketib
Anom selalu ingin agar Alquran dan Hadis menjadi ideologi, ujung tombak
dakwah yang menuntut untuk dilakoni sepersis mungkin. Sementara
kemampuan Mutamakkin melatih diri secara personal terhadap ajaran
tasawuf sebagai pengalaman religius pribadi yang kemudian melahirkan
perilaku yang nyleneh hanyalah pembungkus yang dijadikan penguat oleh
Ketib Anom untuk meyakinkan raja bahwa Mutamakkin telah ‘menyimpang’
dari syariat. “Kiai kok punya anjing, itu kan melanggar ajaran Nabi,”
tegas Ketib Anom.
Tapi
teks Kajen berbicara lain. Pak Latif (41 tahun), salah seorang santri
kiai Sahal Mahfudz bertutur bahwa anjing yang dimiliki Mutamakkin
bukanlah anjing seperti pada umumnya, melainkan simbol pengendalian
nafsu Mutamakkin sendiri. Konon, Mutamakkin pernah melakukan puasa
selama 40 hari tanpa henti. Pada hari ke empatpuluh, Mutamakkin meminta
istrinya untuk menghidangkan beberapa masakan yang enak dan lezat untuk
berbuka. Ketika hidangan tersedia, Mutamakkin sendiri masih berusaha
menahan nafsunya agar tidak tergoda oleh hidangan yang disediakan
istrinya. Lalu ia memerintahkan istrinya untuk memborgol kedua tangannya
supaya ia tidak bebas menyantap makanannya. Ketika itulah, pergulatan
nafsu ingin makan dan keinginan mengendalikan diri menyebabkan nafsu
“buruk” Mutamakkin keluar dari tubuhnya, menjelma menjadi dua anjing
yang menghabiskan hidangan yang ada di depannya. Dan kemudian kedua
anjing ini diberi-nama Kamaruddin dan Abdul Kahar, dua nama yang
menyerupai nama penghulu dan khatib Tuban kala itu.
“Makanya
orang Kajen sendiri, meskipun banyak mengikuti ajaran mbah Mad, tapi
tidak ada yang ikut memelihara anjing. Karena itu bukan anjing biasa,
bukan anjing seperti anjing-anjing yang suka berkeliaran itu. Anjingnya
mbah Mad itu adalah penjelmaan nafsunya sendiri,” jelas pak Latif
kemudian. Meskipun pendapat ini dibantah oleh Muhammad Zuhri yang
mengatakan bahwa anjing Mutamakkin adalah anjing seperti anjing
kebanyakan. Ia bukanlah ciptaan nafsu Mutamakkin. “Begini. Kiai
Mutamakkin itu kan memiliki darah pembauran. Darah Cina seperti
pendahulunya, yaitu Jinbun (Raden Patah). Nama lain Kiai Mutamakkin itu
adalah So Gie. Jadi, sangat wajar kalau beliau itu memelihara anjing,
karena beliau itu seorang Cina, budayawan, sekaligus tokoh spiritual,”
tuturnya.
Masih
menurut Zuhri, penyerupaan nama anjing Mutamakkin dengan nama penghulu
Tuban itu lebih disebabkan oleh tidak amanahnya penghulu tersebut
sebagai pengembang ajaran agama. Contoh, sang penghulu sebagai
koordinator zakat, tetapi tidak pernah menyalurkan hasil zakat itu
kepada fakir miskin. Maka, Mutamakkin mengatakan bahwa perilaku seperti
itu sama saja seperti perilaku anjingnya yang sangat terlihat tamaknya,”
lanjutnya.
Tapi, mungkin juga penamaan tersebut bukan sesuatu yang kebetulan.
Tentu, siapa pun sulit untuk mencari alasan kuat yang menyebabkan
Mutamakkin merasa penting mempertautkan penyerupaan nama tersebut,
kecuali masyarakat Kajen yang memiliki tafsir tersendiri. Bercermin dari
realitas masa kini, masyarakat Kajen seperti halnya Muhammad Zuhri pun
berusaha menggambarkan keadaan masa lalu mengenai hubungan antara
kelompok agama dan negara yang sudah berafiliasi menjadi satu entitas
tunggal. Apa pun agamanya, masuk ke dalam wilayah kekuasaan seringkali
menghilangkan kritisisme terhadap kekuasaan itu sendiri. “Ya kan
kebanyakan orang pemerintahan itu begitu to, Mas. Perilakunya banyak
yang memalukan. Bukan ngayomi, malah nyusahin banyak orang,” ujar pak
Sholeh. Dengan demikian, anjing, versi lain menyebutkan singa, atau yang
lain, oleh masyarakat Kajen justru dijadikan cambuk, kritik, dan
sindiran bagi penguasa atau siapa pun yang merasa bijak mengurusi
kelompoknya tapi kejam menyikap keperbedaan yang lain, seperti
Mutamakkin yang sudah pasti bukanlah mainstream.
Pergeseran-pergeseran Mitis
“Dulu, ketika
saya masih kecil, makam itu tidak ada kuncen-nya. Bahkan, tiap waktu
saya juga bisa masuk ke dalam area makam,” kenang Imam Aziz. Aktifis
yang kini giat mengurusi lembaga Syarikat Yogyakarta dan juga alumnus
Madrasah Mathali’ul Falah ini mengenangkan bahwa ketika kecil ia memang
hampir tiap hari ngaji dan sowan ke pesarean Mutamakkin. Ia pun ingat
bagaimana tempat pesarean itu tidak eksklusif seperti sekarang yang
hanya bisa dibuka untuk umum setiap hari Jumat.
Seperti layaknya kuncen di tempat-tempat lain, juru kunci pesarean
Mutamakkin pun memiliki otoritas tersendiri ketika dihadapkan pada
kenyataan-kenyataan tertentu. Ia dianggap sebagai sosok yang bukan hanya
mampu menjembatani “pertemuan” peziarah dengan Mutamakkin, tetapi juga
menjadi tokoh spiritual yang dianggap memiliki dan memberi barokah
khusus. Bahkan, tidak sedikit orang yang datang berkunjung ke pesarean
Mutamakkin juga sekedar bertemu dengan juru kunci untuk meminta obat
bagi penyakit tertentu dengan menggunakan air yang terdapat di dalam
kamar juru kunci. “Alhamdulillah, dengan perantaraan air ini, banyak
sudah penyakit yang bisa disembuhkan,” tutur pak Sholeh. Bukan hanya
itu, masyarakat seperti pak Sholeh atau juga pak Latief yakin bahwa pada
saat-saat tertentu, khususnya ketika Kajen dan sekitarnya akan
mengalami peristiwa besar, maka anjing Mutamakkin akan menyalak dengan
kencang di malam hari yang suaranya bisa didengar oleh kebanyakan
penduduk. Di samping itu, piring tempat makan Mutamakkin pun masih
disimpan sampai sekarang dan hanya akan diperlihatkan pada hari khusus,
tepatnya ketika haul Mutamakkin itu dilaksanakan. “Piring itu sempat
gompal sedikit karena diperebutkan banyak orang untuk sekedar
menciumnya. Untuk itu, sekarang piring itu hanya bisa dikeluarkan satu
tahun sekali,” cerita pak Sholeh kepada DESANTARA. Kuncen, ”air suci”,
jualan klambu, haul, atau ritual yang lain tentu merupakan bagian dari
minat untuk menghadirkan pesona Mutamakkin agar terasa dekat dan bisa
dirasakan oleh para generasi mutakhir.
Mungkin juga sulit untuk memberi penjelasan secara eksplisit tentang
siapa yang memenuhi otoritas untuk melestarikan pesona mitis yang
dibangun terus-menerus itu, karena di Kajen sendiri terdapat perdebatan
tentang boleh-tidaknya sarana-sarana mitis seperti itu dibakukan. Mbah
Dolah (KH Abdullah Salam), sebagai salah satu keturunan Mutamakkin yang
cukup popular di kalangan ulama dan warga Nahdlatul Ulama (NU) juga
dikabarkan tidak sependapat dengan berbagai ritus mitis yang dilakukan
hanya untuk sekedar melestarikan arwah Mutamakkin.
Menurut Muhammad Zuhri, salah satu tokoh spiritual Kajen,
ketidaksepakatan Mbah Dolah terhadap haul lebih disebabkan karena adanya
perubahan haluan pemaknaan terhadap haul itu sendiri. “Dulu, haul itu
dilestarikan oleh murid-muridnya karena sebagai medium untuk
memanggungkan Dewaruci. Jadi haul sebagai media dakwah,” ujarnya.
Sedangkan saat ini, haul lebih memunculkan nuansa mitis dibanding dengan
pemunculan ide-ide dan kreatifitas pemikiran Mutamakkin. Meskipun
demikian, keturunan Mutamakkin yang lain tetap bersikukuh pada pendirian
untuk melakukan hal yang sebaliknya. Terlepas dari perdebatan para
ahlul bait, yang jelas pesarean Mutamakkin telah menjadi legenda yang
lestari. Dan dari kenyataan seperti ini semakin jelas pula bahwa
penghadiran pesona Mutamakkin seolah-olah bukan hanya ingin dijadikan
sebagai sebuah cerita yang hinggap di benak kepala-kepala individu,
melainkan juga memiliki orientasi rekayasa sejarah di dalam dirinya.
Sejarah bukan hanya cerita, ia hampir pasti memerlukan dukungan
berupa partisipasi aktif, pengetahuan, dan penyebaran nilai-nilai luhur
yang turut memunculkan kebanggaan sekaligus kegemingan bahwa kisah
tentang Mutamakkin lalu menjadi penting untuk dilanjutkan (ditradisikan)
secara terus-menerus. Seiring dengan itu, lambat laun masyarakat
semakin ketat dalam memperlakukan Mutamakkin. Sosok panutan itu disegel
melalui ritual dan semakin beku dalam pola-pola penghormatan yang bukan
hanya mitis, tetapi juga sakral. Anjuran berwudlu sebelum memasuki area
pesarean hanyalah salah satu bagian dari gema wajib yang harus
dilakukan. Asumsi suci menjadi landasan utama bahwa bertemu dengan
Mutamakkin haruslah bersih lahir-batin. Akhirnya, wudlu pun menjadi
ritus yang kental dengan pendisiplinan jiwa dan juga “ancaman” batin
bahwa bagi siapa pun yang tidak berperilaku sopan dan merendahkan diri
–dalam arti suci – maka Tuhan atau mungkin juga (roh) Mutamakkin sendiri
akan murka. Sementara di sisi lain, dan juga pada saat bersamaan, para
pedagang semakin berjejal di sekitar pesarean, tidak hanya sekedar
meraup untung tetapi juga menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya
ulama kharismatik asal Cebolek itu untuk didatangi.
Menyambut Teks Kajen Meninggalkan Serat Cebolek
Tidak
ada ketunggalan kisah yang menyebutkan dari mana Mutamakkin berasal.
Ada yang mengatakan bahwa ulama yang satu ini berasal dari Persia, tapi
ada juga yang mengatakan ia berasal dari Desa Cebolek, Tuban, Jawa
Timur. Mutamakkin juga diyakini sebagai keturunan Sultan Hadiwijaya
(Jaka Tingkir) dan Prabu Brawijaya VI, Raja Majapahit. Meskipun
demikian, penjelasan ini tidak cukup mampu meringkas riwayat hidup
Mutamakkin pada satu titik terang semacam curriculum vitae yang
cukup detil. Satu hal yang hampir pasti adalah bahwa Mutamakkin pernah
belajar beberapa tahun di Timur Tengah lalu bertolak ke tanah Jawa.
Kedatangannya di Kajen pun njebul melek (asal kalimat dari nama
Cebolek, yang artinya muncul secara tiba-tiba lalu membuka mata).
Setelah melakukan pengembaraan ke beberapa tempat, akhirnya Mutamakkin
menetap di Kajen dan melakukan berbagai aktifitas keagamaan, termasuk
berdakwah dan menerima beberapa murid yang di antaranya adalah Kiai
Ronggokusumo, Kiai Mizan, dan Raden Sholeh (keturunan Ki Ageng Selo).
Apa
yang menarik dari kisah Mutamakkin ini adalah kontroversi, stereotip
yang kentara dikukuhkan oleh Yasadipura I di dalam salah satu karyanya
yang cukup terkenal, Serat Cebolek. Karya ini sangat menarik
karena di dalamnya terdapat tuturan yang berkisah tentang usutan Ketib
Anom dan ulama lain terhadap kepercayaan Mutamakkin. Seperti halnya
Jenar, Mutamakkin pun dianggap mengajarkan ilmu mistik. Awalnya, usutan
ulama yang diwakili oleh Demang Urawan sempat ditampik Prabu Amangkurat
IV, raja Kartasura kala itu. “Jangan begitu. Meskipun wajah Mutamakkin
itu tidak rupawan, tapi hatinya suci. Ini suratan takdir, Demang. Ia
adalah pilihan penjaga suksma,” ujar sang prabu sebagaimana tersurat
dalam Serat.
Tentu,
Demang Urawan tersungut, terlebih-lebih Ketib Anom. Konon, ia tetap
mengajukan protes kepada sang raja hingga akhirnya ia diijinkan untuk
menggelar pengadilan khusus membahas masalah Mutamakkin. Seketika Demang
Urawan mengundang Mutamakkin ke keraton. Tapi di tengah perjalanan,
terdengar kabar bahwa raja Amangkurat IV mangkat sehingga pengadilan
atas Mutamakkin tertunda. Setelah tampuk kekuasaan diserahkan kepada
Pakubuwono II, Ketib Anom tetap mendesak raja baru untuk kembali
menindaklanjuti perkara lama yang sempat tertunda. Lagi-lagi, Mutamakkin
kembali diundang yang ia penuhi dengan tenang. Mutamakkin tahu bahwa
Ketib Anom telah mempersiapkan hukuman bakar baginya, tapi ia sama
sekali tidak takut. Bahkan, Mutamakkin sendiri berujar bahwa seandainya
dirinya meninggal karena dibakar, ia justru berharap asapnya bisa
terbang sampai ke Yaman dan bisa dicium oleh gurunya, Syeikh Zen.
Yasadipura I bertutur bahwa di hadapan Ketib Anom dan beberapa ulama yang lain, Mutamakkin diuji untuk membacakan kitab Dewaruci
yang kesohor dan menjadi salah satu kitab kebanggaan Mutamakkin. Tapi
Mutamakkin tidak mampu merampungkan bacaannya lalu dicemooh oleh Ketib
Anom. Mujur, Pakubuwono II masih mengampuni Mutamakkin dengan alasan
bahwa ajaran Mutamakkin adalah laku pribadi dan tidak disebarkan untuk
publik sehingga ia tidak pantas dihukum.
Lain halnya dengan tuturan teks Kajen. Masyarakat sekitar memiliki versi lain, bahwa yang tidak mampu membaca kitab Dewaruci
adalah Ketib Anom sendiri hingga akhirnya meminta bantuan Mutamakkin
untuk merampungkan dan memberi penjelasan tentang kisah yang dimuat di
dalamnya. Mendengar penjelasan Mutamakkin, akhirnya Ketib Anom sadar
bahwa dirinya tidak sebanding dengan kemampuan Mutamakkin, bahkan
Pakubuwono II sendiri akhirnya menyatakan diri sebagai murid Mutamakkin
dan memberi hadiah ulama Cebolek itu untuk menikahi adik Pakubuwono II.
Berkiblat pada tuturan teks Kajen inilah Milal Bizawie (2002) menyimpulkan bahwa fenomena Mutamakkin di dalam Serat Cebolek merupakan kreasi kaum (ulama) elit penjaga syariah sekaligus sebagai cermin dari hegemoni agama keraton, semacam textual politik, demikian
ujar Goenawan Mohamad (2002). Untuk itu, penafsiran yang dimunculkan di
Kajen seyogyanya diapresiasi sebagai kreatifitas lokal atau resistensi
kultural terhadap gempuran wacana yang diisi, disebarkan, dan diikat
oleh kelompok yang untuk sementara menduduki kursi kekuasaan. Tampaknya,
masyarakat pun menyadari bahwa perlawanan bukan berarti harus
mengamandemen teks yang tersurat di dalam Serat Cebolek yang
sudah barang tentu tidak akan efektif, melainkan dengan menghadirkan
kisah lain yang cukup dipedomani sebagai diktat. Alih-alih muncul
kontroversi, tapi yang jelas dan sampai saat ini masih menyisakan jejak
adalah konsistensi masyarakat Kajen yang senantiasa berbondong-bondong
masuk, mampir di pesarean, ngaji, bersimpuh ngalap berkah dengan yakin bahwa Mutamakkin adalah anak zaman yang harus diuri.
“Saya memang membaca Serat Cebolek dan beberapa hasil tulisan orang tentang serat ini.
Tapi saya tidak pernah menjadikannya sebagai pisau analisis untuk
membaca Mutamakkin. Bagi saya tulisan-tulisan itu hanyalah data-data
sejarah yang cukup dijadikan referensi, sementara yang lebih penting
adalah realitas saat ini,” ujar Muhammad Zuhri.
Dengan
demikian, memaknai dan memahami Mutamakkin tidak cukup dengan mengamini
tafsir tunggal Yasadipura I. Tentu, bukan hanya apa yang secara jelas
tersurat di dalam naskah kuno itu yang penting untuk dikaji atau proses
kreatif sang penulis yang menarik untuk dicermati melainkan juga apa
yang saat ini telah menjadi realitas umum yang mengemuka di dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat Kajen. Serat Cebolek hanya
satu versi yang saat ini tidak lagi berdiri sendirian sebagai pengemban
mitos yang tidak bisa dibantah. Di sana terdapat tuturan lain, yang
sudah tentu beda tapi sangat inspiratif untuk dijadikan tempat mengadu
bahkan menyelesaikan kerisauan hati.
Dan mungkin, inilah konteks dimana fenomena Mutamakkin dalam teks Kajen adalah realitas tentang yang aneh, lokal, dan spesifik yang memiliki daya tolak kreatif ketika diperhadapkan dengan kekuatan mainstream
yang cenderung ingin menggerus kekuatan pinggiran. Dan ketika
pergulatan ini semakin menemukan bentuknya dalam pemahaman keseharian
masyarakat, maka kabar dari Serat Cebolek yang banyak
mengundang perhatian para peneliti itu menjadi absurd meskipun pada saat
yang sama, Mutamakkin yang dikabarkan pengagum Dewaruci itu
pun semakin surut dalam pesona yang dibangun dan diabadikan oleh
generasi masa kini yang mudah-mudahan tidak tenggelam dalam kekaguman
yang semata-mata mitis. Tentunya ada rasa khawatir. Ketika keabadian
Mutamakkin hanya disandarkan pada ritual 10 Muharram dan
ditakjubkan sedemikian hebat, maka ia akan berakhir pada pemberhalaan
yang mungkin mengesankan tapi tidak lebih dari sebuah konstruksi.
Sementara peran dan kiprahnya sebagai sosok atau tokoh simbolik –
meminjam istilah Bizawie – “perlawanan kultural agama rakyat” semakin
luntur dari ingatan.